
Pada saat itu, Nabi Musa as. berkata dengan penuh harap,”Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau.” Begitu besar keinginan seorang Rasul yang menjadi pembawa Taurat bagi Bani Israil itu sehingga menggelitik nurani dan keberaniannya untuk melihat Dzat Allah. Kemudian, Allah swt. menjawab,”Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku.” Namun, Allah swt. sangat memahami keinginan hamba-Nya itu dan melanjutkan,”Tapi, lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku.”
Setelah mendengar jawaban Allah swt. tersebut, Nabi Musa as. menunggu dengan penuh harapan. Hanya perasaan bahagia yang bersemayam di dalam hatinya pada saat itu. Ketika tanda-tanda bahwa Allah swt. akan menampakkan Dzat-Nya pada gunung itu, Nabi Musa as. menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri akibat dari permohonannya. Tatkala Allah swt. menampakkan diri-Nya kepada gunung itu—para mufassirin mengartikan bahwa yang nampak itu hanya kebesaran Allah, sebagian lainnya mengatakan bahwa itu hanyalah Nur Allah—maka gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa as. jatuh pingsan. Setelah Nabi Musa as. sadar kembali, beliau serta merta mengakui kesalahannya dan berkata,”Maha Suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman.” Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
Kisah tersebut menggambarkan bagaimana kerinduan seorang hamba (Rasul) kepada Tuhannya sehingga hanya pertemuan langsung yang diinginkannya. Nabi Musa as. kalamullah sudah diberikan mukjizat untuk dapat bercakap-cakap langsung dengan Allah swt., akan tetapi kerinduannya yang paling mendalam adalah berjumpa dengan Allah. Kerinduan Nabi Musa as. itu bukanlah suatu harapan yang salah dalam pandangan Allah swt., namun tataran hakikat perjumpaan yang diinginkannya berada jauh di atas kemampuan manusiawi beliau.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan Nabi Musa as. itu juga berkecamuk di dalam dada setiap kaum mu’min. Hati yang senantiasa dalam kerinduan—sebagai ciri adanya kecintaan hamba—untuk berjumpa dengan Allah swt. berkata,”Aku ingin melihat Allah.” Allah swt. tidak melupakan gejolak rasa kerinduan hamba-Nya itu dan Islam adalah jawaban langsung dari Allah swt. atas keinginan tersebut.
Islam yang diturunkan Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. sebagai rahmatan lil ‘alaamin, sama sekali tidak mengabaikan rasa kerinduan itu. Agama yang mulia ini memberikan kesempatan emas tersebut dalam berbagai konteks yang telah diajarkan secara komprehensif, namun lugas dalam penyampaiannya. Setiap kaum mu’min berhak untuk melihat Allah swt. dalam segala situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam paket-paket eksklusif suatu ibadah tertentu.
Rasulullah saw. telah mengajarkan cara yang efektif untuk melihat Allah swt. Berdasarkan salah satu hadits yang disampaikan oleh Umar ra. ketika Malaikat Jibril mendatangi mereka (Rasulullah saw. dan sahabat) untuk menjelaskan arti agama kepada para sahabat. Percakapan antara Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad saw. memberikan kesimpulan bahwa agama (ad-diin) adalah kesatuan antara perilaku ibadah, keimanan, dan kesungguhan hati dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah hadits yang menjelaskan mata rantai agama tersebut.
Pada suatu hari ketika kami (sahabat) sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw., datanglah seorang laki-laki yang sangat putih warna kulitnya dan rambutnya hitam legam. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa orang itu baru saja datang setelah melakukan satu perjalanan jauh. Tidak ada pula seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Orang itu duduk persis di hadapan Nabi saw. dengan menumpangkan kedua lututnya di atas lutut Nabi saw dan menekankan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi saw., seraya bertanya,”Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam.” Nabi menjawab,”Islam ialah, mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji jika sanggup melakukannya.” Setelah mendengar jawaban Nabi saw., orang itu berkata,”Benar, seperti jawaban Anda ini.” Umar berkata,”Kami heran, orang itu bertanya dan membenarkan jawaban yang Nabi saw. berikan.”Orang itu mengajukan pertanyaan lagi,”Terangkanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan Iman.” Nabi saw. menjawab,”Iman adalah yakin percaya akan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan qadha serta qadar Allah.” Orang itu berkata,”Benar seperti yang Anda katakan.” Kemudian orang itu bertanya lagi,”Terangkan pula kepadaku, apakah yang disebut ihsan?” Nabi saw. menjawab,”Ihsan ialah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika engkau merasakan tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.”… (Shahih Muslim).
Konsep ihsan yang dijelaskan dalam hadits di atas menjabarkan tentang pemahaman yang unitif dan menyeluruh terhadap aktivitas spiritual kita. Pada percakapan antara Malaikat Jibril dengan nabi Muhammad saw. sebelumnya, yaitu pertanyaan Ruhul Qudus (Malaikat Jibril) tentang hakikat Islam, Nabi Muhammad saw. mengatakan bahwa esensi Islam terdapat pada pilar-pilar Rukun Islam yang terdiri atas lima aktivitas spiritual yang fundamental, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan shalat fardhu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sementara itu, perihal substansi komplementer dari lima aktivitas spiritual pokok tersebut adalah Rukun Iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar Allah. Integrasi dua konsep primordial itu berimplikasi pada pembentukan perilaku ibadah yang ihsan, yaitu kesungguhan beribadah yang memberikan indikasi adanya perasaan melihat Allah swt.
Kemudian, Nabi saw. melanjutkan bahwa apabila seorang hamba tidak merasakan melihat Allah, maka ia harus yakin bahwa Allah melihatnya. Pernyataan ini seakan bermakna mendistorsi pola keyakinan seorang abid dari konteks “melihat Allah” pada tuturan Nabi saw. sebelumnya, menjadi “dilihat Allah”. Sekilas, dua konteks itu adalah dua situasi yang bertentangan. Namun jika diperhatikan secara seksama wasiat Rasulullah saw. pada kalimat,”Yakinlah, bahwa Allah melihatmu”, sebenarnya adalah bentuk fundamental tentang bagaimana cara melihat Allah, yaitu dengan cara melihat (merasakan) sifat As-Sami’ dan al-Bashir dari Allah swt.
Mata rantai konseptual bagaimana melihat Allah swt. tersebut, bukanlah isapan jempol semata. Apabila seorang hamba benar-benar memahami makna batiniah dari setiap aktivitas spiritual yang dilakukannya, maka ia akan dapat melepaskan kerinduannya kepada Allah swt. dan sekaligus mampu melihat Allah swt. dengan kebersihan hatinya. Contohnya adalah pada saat seorang hamba melakukan ibadah shalat. Dengan memahami makna setiap bacaannya dan menjaga kekhusyukannya, bukan tidak mungkin ia dapat berjumpa dengan Allah swt. Bahkan kegelisahan, ketakutan, dan rasa sakit sekalipun tidak akan sanggup mengganggu perjumpaan tersebut. Sudah pasti, kondisi itulah yang dirasakan oleh Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib ra. ketika anak panah yang menancap ditubuhnya harus dicabut, dan beliau meminta para sahabat untuk melakukan itu ketika ia sedang shalat.
Dalam riwayat sirah Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib ra. lainnya, beliau juga pernah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana melihat Allah swt. Seorang laki-laki yang bernama Dzi’lib Al-Yamani, sangat menginginkan perjumpaan dengan Allah swt. Dengan langkah pasti, ia menghadap Sayidina ‘Ali r.a. untuk meminta petunjuk agar ia terlepas dari kerinduannya tersebut.
Ketika Dzi’lib Al-Yamani bertemu dengan Sayyidina ‘Ali r.a., ia bertanya kepada beliau,”Dapatkah Anda melihat Tuhanmu wahai Amir al-Mukminin?” Jawab Sayidina ‘Ali r.a.,”Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?” Orang itu bertanya lagi,“Bagaimana Anda melihat-Nya?” Kemudian, dengan wajah yang penuh keikhlasan, Sayidina ‘Ali memberikan penjelasan sebagai berikut.
“Dia (Allah) takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh oleh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan. Jauh tanpa jarak. Berbicara tanpa harus berpikir sebelumnya. Berkehendak tanpa perlu berencana. Berbuat tanpa memerlukan tangan. Lembut tapi tidak tersembunyi. Besar tapi tidak teraih. Melihat tapi tidak bersifat inderawi. Maha Penyayang tapi tidak bersifat lunak. Wajah-wajah merunduk di hadapan keagungan-Nya. Jiwa-jiwa bergetar karena ketakutan terhadap-Nya.”
Simplifikasi yang gamblang oleh Imam ‘Ali r.a. membuat laki-laki itu berpikir dan tertunduk sebagai tanda bahwa ia paham. Sebuah analisis derivasi dari konsep yang sulit, yaitu melihat Allah, menuju bentuk penyederhanaan konsep yang mudah dipahami telah dijelaskan oleh Sayidina ‘Ali bin Abi Thalib melalui sirah tersebut. Beliau menyampaikan sebuah sinopsis bahwa melihat Allah adalah melalui Sifat-Sifat dan Nama-Nama Suci Allah swt.
Pada setiap waktu dalam setiap kesempatan, kita dapat melihat Allah swt. melalui pemaknaan yang mendalam terhadap Kebesaran Allah swt. yang terkandung dalam 20 Sifat Wajib Allah dan 99 Asma’ul Husna yang hanya dimiliki-Nya. Hal itu merupakan tataran perjumpaan yang diperkenankan-Nya untuk kehidupan di dunia ini. Namun demikian, tingkatan perjumpaan pada tataran ini bukanlah suatu bentuk pertemuan yang berseberangan makna dengan perjumpaan langsung kepada Allah swt., karena hakikat Dzat Allah adalah Sifat dan Nama Allah itu sendiri. Jadi, apabila seorang hamba mampu melihat Allah swt. melalui Sifat dan Nama-Nya yang Maha Mulia, maka ia telah “bertemu” dengan Dzat Allah.
Berdasarkan pemahaman, internalisasi, dan aktualisasi Kebesaran Allah swt. tersebut di dalam setiap aspek kehidupan kita maka kaum mu’min akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah swt. Lebih dari itu, diiringi dengan keteguhan hati serta istiqomah di dalam Islam, maka insya Allah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dibimbing Allah swt. untuk mendapatkan cahaya-Nya (QS. 24:35). Barangkali, kenikmatan ini dapat direnungkan sebagai sebagai salah satu anugerah terbesar yang pernah diberikan Allah swt. kepada umat Nabi Muhammad saw.
Tentu saja premis tersebut dimaknai tanpa mengabaikan (menyalahkan) sirah Nabi Musa as. yang pernah bertobat atas kesalahannya terhadap keinginan yang sama—namun pada tataran hakikat perjumpaan yang berbeda. Setiap kaum mu’min dapat mengambil hikmah bahwa Allah swt. benar-benar memuliakan umat Nabi Muhammad saw. dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk berjumpa dengan-Nya. Inilah yang menjadi bukti kecintaan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya. Hal itu diindikasikan dengan diberikannya pedoman yang jelas oleh Allah swt. di dalam Al-Qur’an, melalui hadits Rasul-Nya, ataupun perantara lidah para sahabat dan ulama-Nya tentang bagaimana melihat Allah swt. dengan segala keterbatasan kemampuan manusiawi kita. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa as. atas keinginan beliau untuk melihat Dzat-Nya secara langsung selama masih berada di dunia ini.





.jpg)

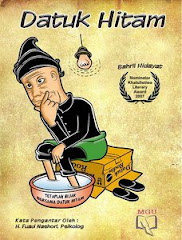

1 komentar:
punya buku tentang tafsir al mufaddhol nggak ?
Posting Komentar