Fragmen Memoar Aku Tahu Gila (2008)
....
Waktu berjalan menapaki hari demi hari. Pada pertengahan Maret 2007, keluhan gejala positif itu mucul dan kuceritakan pada Indri sepulang dari mengajar sebagai dosen honor di Fakultas Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Pekanbaru. Sore itu, aku ceritakan semuanya di kamar tidur kami, di sisi timur yang lapang dari ranjang pengantin kami.
”Peluk Abang, Dek,” pintaku dengan suara bergetar.
”Peluk Abang...”
Serta merta Indri memeluk punggungku. Dia mengelus tangan kananku yang masih saja memeluk erat bantal guling. Cengkeraman tanganku ke guling itu menunjukkan rasa takut yang besar saat gejala-gejala halusinasi itu datang.
Aku merasa tubuh ini dingin dan gemetar. Nafasku sesak seperti terserang malaria. Keringat dingin mengalir deras dari sekujur tubuh, padahal kamar Air Conditioner di kamar tidur kami sudah dinyalakan dengan suhu minimal, enam belas derajat celcius.
”Gimana, Bang? Sudah lebih enak?” tanya Indri.
“Iya, Dek. Tapi suara itu masih ada.”
“Nggak apa-apa Bang. Abaikan aja suara-suara itu, ya.”
“Iya, Dek.”
“Abang tahu.”
Kami diam sejenak. Nafasku mulai terkendali. Rileksasi sederhana dengan menarik nafas dalam-dalam, menahannya beberapa hitungan, lalu dihembuskan perlahan. Rileksasi itu sering aku terapkan jika gejala halusinasi mulai menyerang, baik sekadar berupa ide-ide di dalam kepala maupun jika sudah menjelma menjadi auditory atau visual halusinasi yang punya otoritas terhadap penderita skizofrenik.
“Abang bisa atasi ini? Atau Adek suntikkan Serenace lima miligram?” tanya Indri lembut. Dia tahu tabiatku yang tegas untuk memilih saat yang tepat kapan harus menggunakan psikofarmakologis, kapan harus mengatasi gejala positif skizofrenik paranoid ini melalui psikoterapi.
”Nggak. Nggak perlu, Dek.”
”Abang perlu Adek peluk. Itu aja,” sambungku dengan suara yang lebih tenang.
”Iya, Bang,” Indri terus memeluk punggungnya. Aku selalu membelakanginya jika gejala itu datang. Mungkin saja karena aku malu atau tidak ingin membuatnya dengan memperlihatkan wajahku.
”Abang seperti mayat berjalan kalau pake obat psikiater,” keluhku.
”Iya, Adek tahu. Makanya Adek percaya kapan Abang harus gunakan obat itu, kapan tidak.”
”Adek percaya sama Abang,” tangankunya menggenggam punggung tangan kananku. Aku berusaha lepaskan genggaman tangan ini dari guling itu dan menggantikan tangannya sebagai kekuatan yang menggenggam jiwaku saat itu.
”Makasih, Bunda...” ucapku lirih dengan panggilan khasku kepadanya di depan anak kami, Layla.
”Makasih...”
Aku membalikkan tubuh dan meletakkan wajah yang pucat di lehernya. Lehernya basah oleh keringat. Keringat dingin kami bercampur dalam pelukan itu. Di bawah tempat ia bersandar itu, dadaku tengah bergemuruh dengan ribuan doa agar Allah swt. memberikan pertolongan kepada kami saat itu.
Alunan doa yang selama ini setia menemani kami sejak awal menikah. Aku juga merasakan Indri melakukan hal yang sama. Bait-demi bait doa pengaduan kepada Allah tentang keluh kesah hati ini saat aku melewati fase-fase serangan gejala skizofrenik dengan memukul meja, lemari, atau apapun yang berada di dekatku dan sering berkata ketika gejala itu datang, ”Dia datang lagi. Dia datang lagi...” sambil mondar-mandir tak karuan.
Selain itu, pelukan adalah senjata ampuh meredakan halusinasi ini. Setiap kali aku merasakan goncangan akibat menundukkan gejala positif skizofrenik berupa delusi dan halusinasi, Indri memelukku dengan erat, sesekali melemahkan pelukannya agar aku bisa bernafas dengan lega. Ibarat pelukan sang ibu untuk meredakan tangis anaknya, demikian pula pelukan Ibuku ketika salah satu halusinasi menyerang, yaitu aku melihat ratusan lipan ingin menggigitku. Ibarat pelukan Jibril kepada Nabi Muhammad saw. ketika wahyu pertama turun dan akibatkan goncangan mental kepada Nabi saw., demikian pula harapan pelukan Indri untukku. Seperti harapan Jibril menenangkan Nabi saw. dengan tiga kali pelukan dan akhirnya beliau mampu membaca surah al-’Alaq itu dengan tenang, demikian pula ketegarannya untuk memelukku berulang kali agar aku memeroleh ketenangan di waktu gejolak halusinasi itu berusaha menaklukkan kesadaranku.
”Halusinasi itu datang lagi, Dek,” ucapku lirih.
”Semakin jelas dan mulai menguasai,” keluhku lagi dengan mata berbinar, tapi sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya.
Aku genggam jemarinya. Aku paksakan seuntai senyum untuk menyemangatinya dengan segurat diam. Aku ingin menjadi pendengar yang baik untuknya, bukan sebagai penasihat pribadinya.
”Tadi waktu Abang mengajar, abang melihat sekelebatan orang mengintip dari pintu ruangan kelas Abang ngajar.”
”Itu sangat mengganggu...”
Aku diam. Lalu Indri coba mengupas emosiku.
“Iya, Bang. Kemudian gimana ceritanya?”
“Abang kejar orang yang mengintip itu ke arah pintu. Tapi rupanya nggak ada.”
“Abang mulai cemas…”
“Dan yakin…” aku terdiam lagi.
“Yakin apa, Bang?” tanya Indri mulai tertular kecemasan dariku.
“Yakin kalo itu halusinasi,” aku menunduk dan mataku basah. Sulit bagi laki-laki seperti aku untuk tidak menangis di saat sulit seperti ini.
”Kemudian Abang juga mendengar suara yang mengejek itu lagi.”
”Riuh...”
”Mereka ketawa...”
”Mengejek lagi...”
”Berbisik-bisik...”
”Ada anak-anak, perempuan, dan satu suara itu yang sangat Abang kenal,” aku menarik nafas.
”Suara siapa, Bang?”
”Suara laki-laki yang berat dan tegas. Nge-bass. Dia suruh abang untuk menggantung leher.”
”Atau mencuri pistol polisi, terus meledakkan kepala Abang dengan pistol itu,” tanganku lepas dari genggamannya.
”Terus abang malu sama mahasiswa di kelas itu. Abang merasa mereka tahu yang sedang Aang alami.”
”Untuk tutupi halusinasi itu, Abang bilang sama mereka, kalo maag abang kambuh. Tapi Abang rasa mereka juga tahu halusinasi itu,” keluhku dengan perasaan bersalah yang berpendar dari matanya.
Suasana hening. Indri menunduk. Dia agak bingung harus melakukan apa untuk menenangkanku, tapi berusaha berada di sampingku. Itulah pengetahuannya yang luar biasa untuk beri dukungan kepadaku, meskipun hanya berupa diam karena bingung.
”Dek, Abang merokok lagi ya. Abang nggak tahan dengan kondisi ini. Mungkin rokok bisa membantu Abang supaya nggak tegang.”
”Iya Bang. Sebentar ya,” dia keluar dari kamar dan berusaha mencarikan rokok untukku.
Indri berjalan dan berusaha memahami kondisiku saat itu. Beberapa bulan setelah pernikahan Indri memintaku berhenti merokok dan aku katakan akan berhenti setelah anak kami lahir. September 2004 lalu aku menepati janji itu dan sudah berhenti merokok selama enam bulan ini. Tapi, pada bulan Maret 2005 ini, aku membutuhkan rokok dan meminta izin kepada Indri.
Lalu Indri kembali ke kamar setelah menemukan sebungkus rokok di meja ruang keluarga. Entah rokok siapa itu, aku tak peduli. Boleh jadi rokok abang iparku yang tertinggal tadi siang waktu ia berkunjung ke sini.
”Ini, Bang. Nggak apa-apa Abang merokok lagi. Tapi jangan banyak-banyak ya. Sayangi kesehatan Abang, Adek, dan Layla,” Indri tersenyum padaku sambil serahkan sebungkus rokok dan korek api gas.
Aku mengangguk. Dengan tangan yang gemetar, aku membakar rokok itu dengan tergesa-gesa.
”Uhuk...uhuk...”
”Pelan-pelan Bang,” bujuknya.
”Ini minum dulu,” Indri ulurkan segelas teh panas yang memang sudah diseduh untukku sesaat setelah shalat Ashar sore itu.
Teh itu aku minum dengan perlahan. Seteguk demi seteguk, teh hangat itu mmbasahi tenggorokan yang panas karena sudah enam bulan tidak merokok dan terkejut dengan kebiasaan lama itu yang terulang lagi.
”Makasih, Dek,” ucapku tulus dengan segurat senyuman yang sejak tadi dia tunggu. Indri membalas senyumanku yang miris.
”Abang rasa, Abang harus berhenti mengajar.”
”Abang nggak mungkin mengajar dalam keadaan seperti ini,” sambungku lirih.
”Iya. Adek dukung keputusan Abang itu.”
“Tapi kasihan mahasiswa. Abang tinggalkan mereka di tengah semester,” keluhku lagi. Lalu jari yang gemetar kembali menaruh rokok itu ke celah bibirku.
”Abang jangan pikirkan itu. Kampus pasti punya solusinya. Mungkin dengan cari dosen pengganti untuk mata kuliah itu.”
”Yang penting Abang fokus untuk atasi gejala ini. Mungkin udah saatnya Abang konsumsi obat psikiatri lagi,” bujuk Indri.
”Nggak. Itu nggak mungkin!” tiba-tiba aku marah mendengar kalimat itu.
”Adek pengen Abang jadi mayat berjalan lagi?”
”Nggak bisa beraktivitas? ”
”Nggak bisa nulis?”
”Nggak bisa main sama Layla?” cecar tanya yang mengandung amarah pun mengalir dari mulutku.
”Iya, Bang. Adek ngerti.”
”Oya? Adek ngerti?” aku bertambah marah.
”Adek mengerti perasaan Abang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban lahir dan batin sama Adek karena obat sialan itu?” hujam pertanyaan itu ke ulu hatinya.
Tiba-tiba Indri menangis. Air mata yang sudah ditahannya sejak tadi tidak terbendung lagi. Dia menjatuhkan kepala di pangkuanku.
”Adek minta maaf, Bang,” pintanya di pangkuanku.
”Nggak. Adek nggak salah,” suaraku mulai parau.
“Ehm…”
“Adek nggak perlu minta maaf,” ucapku lembut dengan mengelus rambut Indri.
“Abang bisa atasi gejala ini dengan psikoterapi, terapi Islam, dan akan gunakan obat jika memang Abang butuh,” lanjutku.
Indri hanya mengangguk di pangkuanku meskipun aku sebenarnya tahu tidak mungkin bagi penderita skizofrenik untuk atasi gejala positifnya tanpa obat psikofarmakologis. Dan aku tahu Indri cuma berusaha mengiyakan semua keinginanku yang wajar saat itu agar aku tenang. Biarkan waktu yang menentukan kesadaran ini agar bersedia menjalani terapi psikofarmakologis lagi melalui obat dari psikiater. Di balik itu semua, Indri yang rebah di pangkuan bisa memberikan ketenangannya yang mengalir melalui belaian lembut tanganku di rambutnya yang ikal.
…





.jpg)

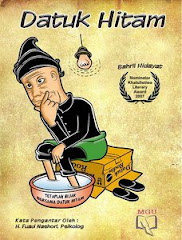

Tidak ada komentar:
Posting Komentar